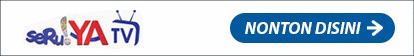Bersama waktu tuhan terkadang mempertemukan kita dengan orang yang tak disangka-sangka. Termasuk dalam pendakian kali ini. Salah satu cucu Nene Mori (Nenek Mori) rupanya ikut ambil bagian menapaki jejak-jejak leluhurnya yang berdampingan dengan puncak tertinggi ‘Tanah Bahagia’, Rante Mario (3478 mdpl)
Legenda Nene Mori (Nenek Mori) hingga kini hidup di kepala pendaki. Dikenal sebagai manusia digdaya, pemburu Anoa. Namanya diabadikan pada satu puncak yang disebut Puncak Nene Mori dengan ketinggian 3397 mdpl.
CATATAN: Muhammad Nursaleh
Bukan satu kebetulan, dalam pendakian ini tuhan mempertemukan kami dengan salah satu cucu Nene Mori. Namanya Idil. Masih muda. Usianya 26 tahun. Semula kami mengenalnya hanya sebatas sebagai warga Dusun Gamaru, Latimojong yang menawarkan diri ingin ikut serta dalam pendakian.


Tak pernah sekali pun Idil menjelaskan kaitan dirinya dengan Nene Mori. Bahkan hingga memasuki dua hari perjalanan, ia malah lebih banyak bercerita tentang keinginannya membentuk komunitas pecinta alam di wilayah Latimojong, Luwu. Atau lain waktu membahas perlengkapan pendakian yang belum sepenuhnya ia miliki.
Barulah saat rehat di tengah perjalanan menuju pos 5, saat kami membincang soal Nene Mori, Idil spontan menyebut dan memperkenalkan dirinya sebagai cucu asli dari trah Nene Mori. Benarkah ? Idil kemudian bercerita.
“Itu nenek saya. Bapak dari bapak saya. Bapak saya dulunya juga seorang pemburu. Dan cucu Nene Mori, Si Mori, sepupu saya yang ada dalam cerita yang berkembang selama ini, sekarang tinggal di Gamaru. Sekarang Mori bekerja menggarap kebun. Kuburan Nene Mori berada di wilayah Sarasa Gamaru”.
Kulihat istriku terperangah. Aku pun sesungguhnya demikian, hanya berupaya bersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan yang kualamatkan ke Idil. Ia begitu mengetahui dan memahami legenda neneknya yang selama ini telanjur melekat di masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pegunungan. Termasuk para pemburu Anoa, binatang endemik Sulawesi.
Dalam legenda, konon Nene Mori berburu tidak memakai senjata. Ia hanya melantunkan kidung untuk Anoa-Anoa yang berkeliaran di hutan sekitar gunung tersebut. Bila ingin memulai perburuannya, Nenek mori cukup melantunkan kidung di atas sebuah batu besar di puncak gunung. Suaranya yang menggema terpantul di dinding gunung dan lembah mengalun seolah mengajak dan menawarkan persahabatan. Seketika Anoa pun berdatangan dengan jinak kemudian menghampirinya.
Batu besar yang digunakan Nene Mori berkidung inilah yang diabadikan sebagai nama Puncak Nene Mori.
Darah pemburu memang mengalir di tubuh Idil. Bayangkan, berjalan di jalur tanjakan, ia hanya seperti berjalan di atas tanah datar. Gerakannya sangat cepat walaupun pundaknya membawa beban berat. Ia pandai membaca lintasan jalur dan mengetahui benar tumbuhan yang layak untuk dikonsumsi bila di dalam hutan.
Dan yang paling mencengangkan dalam pendakian ini, Idil berani mengganti batu puncak yang terpasang pada triangulasi (tiang besi). Sesuatu yang tabu dilakukan dalam wilayah Nene Mori. Ia malah tersenyum setelah selesai melakukannya.
“Lihat, bang ! Batunya sudah saya ganti. Masa puncak nenek saya, batunya kecil. Sekarang sudah besar”. Aku tak berani berbicara. Hanya menyilahkan istri segera menyentuh dan berfoto di samping triangulasi Nene Mori.
Satu jam lagi malam tiba. Suhu dingin semakin menggila, suara angin seolah suara raksasa murka. Kami meninggalkan Nene Mori. Meninggalkan sebuah legenda sekaligus aura mistik yang meliputinya.
Menuju telaga. (***/Bersambung…)